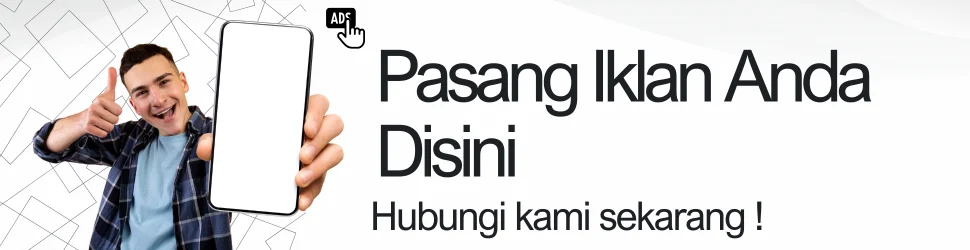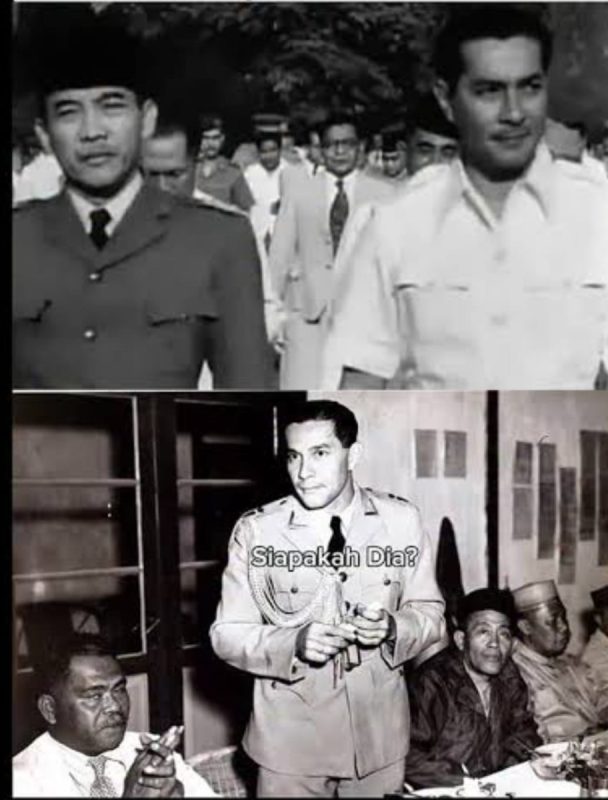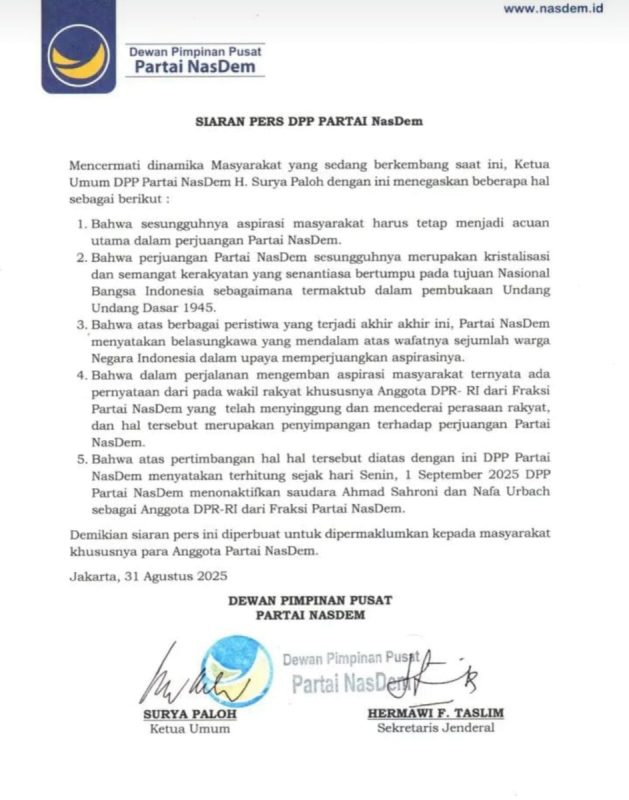Oleh: Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman Nur
Salam sejahtera, salam budaya, salam Pancasila. Mari kita ngopi dulu, wak, dengan kopi liberika, lalu kita bertanya: ape bende sebenarnya Sertifikat K3, sampai-sampai seorang pejabat negara, bahkan seorang Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel, diduga tega memeras perusahaan?
K3 dalam Bingkai Hukum, sebenarnya K3 adalah singkatan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ia bukan sekadar aturan teknis, tapi merupakan hak asasi pekerja sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diperkuat dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3
Dalam semiotika hukum, K3 adalah tanda peradaban hukum kita: Bahwa setiap pekerja berhak pulang selamat ke rumah. Bahwa setiap perusahaan wajib membangun sistem yang melindungi nyawa, bukan sekadar keuntungan. Bahwa negara hadir untuk memastikan keselamatan bukan hanya jargon, melainkan tanggung jawab hukum
Sertifikat sebagai Tanda, Sertifikat K3 adalah tanda legal. Ia terdiri dari stempel, tanda tangan, nomor registrasi, QR code. Tetapi dalam semiotika, tanda bukan hanya bentuk—ia memuat makna dan efek hukum.
Makna formil: “Pemegang ini kompeten.”Efek hukum: boleh mengoperasikan crane, memimpin pekerjaan ketinggian, atau memastikan pabrik kimia tidak meledak.mIkon hukum: sertifikat itu menjadi simbol negara yang hadir di tempat kerja.Maka, sertifikat itu bukan sekadar kertas. Ia adalah tindak performatif: begitu ditandatangani, status berubah dari “tidak boleh” menjadi “boleh.”
Paradoks Biaya dan Prosedur,
Proses mendapatkan sertifikat tidak sederhana: pelatihan 12–15 hari, ujian teori dan praktik, audit dokumen, hingga tanda tangan pejabat. Biaya pelatihan resmi di pasar berkisar Rp 3–7 juta per orang, berbeda dengan tarif negara (PNBP) yang hanya Rp 275 ribu. Namun, dalam praktiknya, muncul perbedaan besar. Menurut KPK, buruh dan perusahaan diperas hingga Rp 6 juta hanya untuk mempercepat sertifikat yang seharusnya bisa keluar dengan biaya resmi. Inilah ruang gelap di mana tanda hukum—sertifikat—bergeser makna: dari bukti kompetensi menjadi tiket berbayar
Kasus Noel: Kerusakan Makna, OTT KPK pada 20 Agustus 2025 membongkar dugaan pemerasan ini. Noel, Wakil Menteri, disebut tahu praktiknya sejak 2019, namun bukan melawan, malah ikut meminta bagian. KPK menyebut setidaknya ada dana Rp 3 miliar yang mengalir kepadanya. Dalam semiotika hukum, ini bukan sekadar tindak pidana. Ini adalah kerusakan tanda. Sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja, kini dimaknai ulang sebagai alat rente dan pemerasan. Bahasa hukum patah: yang semestinya berarti kompeten & aman, kini berarti bisa bayar & dekat dengan pejabat.
Semiotika Hukum: Membaca Simbol
1. Simbol otoritas, Sertifikat adalah simbol legitimasi negara. Jika simbol ini rusak, kepercayaan publik runtuh.
2. Ritual legal, Pelatihan, ujian, audit adalah ritual yang menciptakan makna. Bila ritual ini dipotong dengan uang, makna hilang, tanda kosong.
3. Mitos keselamatan, Masyarakat percaya: “Ada sertifikat = aman.” Padahal, keselamatan bukan kertas, melainkan budaya kerja. Sertifikat palsu adalah mitos kosong.
4. Ekonomi tanda,Saat biaya resmi rendah tetapi nilainya tinggi bagi perusahaan, tanda berubah menjadi komoditas. Harga gelap Rp 6 juta bukan membeli ilmu, melainkan membeli akses.
5. Form vs substance, Bentuk (sertifikat) tetap ada, tetapi substansi (keselamatan nyata) hilang. Inilah tragedi: dokumen sah, tapi pekerja tetap rentan celaka.
Solusi: Menjinakkan Ambiguitas, Dalam kerangka semiotika hukum, masalah ini bukan sekadar menindak pelaku, tetapi mereformasi tanda.
- Pisahkan jelas biaya pelatihan komersial dan biaya resmi negara.
- Sertifikat digital verifiable, lengkap dengan metadata: siapa penguji, kapan, hasil berapa.
- Audit trail terbuka: setiap langkah pemrosesan transparan, publik bisa menagih SLA.
- Blind review & sistem acak: agar kedekatan personal tak memengaruhi tanda.
- Publikasi data: rata-rata waktu penerbitan sertifikat dan outlier jadi informasi publik.
- Bahasa risiko: kampanye “Ape Bende K3?” harus mengajarkan bahwa sertifikat bukan jimat, melainkan tanggung jawab nyawa.
Pesan Moral, dari kasus atau peristiwa hukum diatas , bahwa Sertifikat K3 adalah ikon peradaban hukum modern. Ia mengingatkan bahwa hukum hadir untuk melindungi manusia. Ketika sertifikat itu diperdagangkan, kita bukan hanya menghadapi korupsi birokrasi, tapi pembusukan makna.
Menurut pengamatan saya Sebagai Tengku Mulia Dilaga, saya ingin menegaskan: K3 bukan formalitas, bukan komoditas, tapi komitmen moral dan hukum. Jika kita gagal menjaga makna tanda ini, kita sedang menggadaikan nyawa pekerja untuk selembar kertas. Maka, marilah kita rawat tanda hukum ini agar tetap setia pada maknanya. Biarlah sertifikat K3 kembali menjadi simbol yang benar: pekerja selamat, perusahaan bermartabat, dan negara berintegritas.
“Ape Bende” Sertifikat K3: Membaca Skandal Noel lewat Semiotika Hukum, Mari kita mulai dengan kopi liberika dulu, wak. Lalu kita tanya: ape bende sebenarnya “Sertifikat K3” sampai-sampai (diduga) bisa diperas, disandera, dijadikan komoditas? Dan bagaimana semiotika hukum—ilmu tentang tanda, makna, dan praktik hukum—membantu kita membacanya?
Kilas Fakta (biar tak salah urat), 22 Agustus 2025, KPK menetapkan 11 tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan; termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel). KPK menyebut biaya resmi sertifikasi Rp 275 ribu, namun di lapangan buruh/ perusahaan dipaksa membayar sampai Rp 6 juta dengan modus memperlambat atau tak memproses berkas bila tidak “nambah”. KPK juga memaparkan aliran dana dan menyebut praktiknya berlangsung sejak 2019, dengan dugaan akumulasi mencapai puluhan miliar rupiah; Noel diduga menerima sekitar Rp 3 miliar pada 2024. (Semua masih proses hukum & asas praduga tak bersalah berlaku.)
Legal frame dasar K3: UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (payung utama) dan PP No. 50/2012 tentang SMK3 (sistem manajemen). Regulasi teknis K3 bertebaran di Permenaker untuk berbagai skema kompetensi/alat/lingkungan kerja.
Biaya pelatihan Ahli K3 Umum (di pasar) memang tidak murah; banyak penyelenggara mematok ± Rp 3–7 juta/peserta (bisa lebih tinggi untuk paket/offline tertentu)—ini biaya pelatihan komersial, beda dari PNBP penerbitan sertifikat yang jadi rujukan “biaya resmi” KPK. Sampai sini, “Camane orang Kemenaker, betul ndak?”
Garis besarnya: K3 itu wajib secara hukum dan sertifikasinya menjadi prasyarat legal pada banyak jenis pekerjaan. Yang bikin gaduh adalah gap antara biaya/ prosedur resmi vs. biaya bayangan karena jalur birokrasi yang dipersempit—di situlah, kata KPK, praktik pemerasan muncul.
Analisis lebih dalam , bahwa Semiotika Hukum: Membaca “Sertifikat” sebagai Tanda Di semiotika (Saussure/Peirce), tanda selalu punya bentuk (signifier) dan makna (signified), serta interpretant (cara publik menafsirkannya). Dalam hukum, tanda bukan cuma tulisan di kertas; ia mengubah status—mirip “kata-kata performatif” ala teori tindak tutur: begitu stempel/QR/nomor registrasi ditempel, status hukum pemegangnya berubah dari non-kompeten/ tak boleh menjadi kompeten/ boleh. Itulah daya illocutionary dari sertifikat.1) Sertifikat K3 sebagai simbol otoritas, Bentuk: nomor, logo Garuda, tanda tangan pejabat, QR code, basis data.Makna: “orang ini kompeten”, “perusahaan ini patuh”. Efek hukum: boleh mengoperasikan crane, mengelola bahan kimia, mengajukan tender, lolos audit.
Jika kita gunakan analisis Semiotika hukum dalam kacamata Peirce, sertifikat berfungsi simbolik (bermakna karena konvensi hukum), sekaligus indeksikal (menunjuk riwayat pelatihan/ujian/asesmen), dan kadang ikonik (desain/format resmi yang “mirip” dokumen negara).
Ritual legal sebagai produksi makna, Pelatihan, ujian, audit, berita acara, tanda tangan pejabat—semuanya adalah ritual hukum yang membangun legitimasi. Ketika satu mata rantai “dipetik” (diputar, dipercepat, disandera), maknanya bergeser: dari jaminan mutu menjadi komoditas akses. Maka bukan sekadar pelanggaran etik; ini perusakan semiotik—tandanya masih tampak sah, tapi maknanya kosong.
Mitos modern: “Ada sertifikat = sudah aman” jika kita gunakan analisis Barthes menyebut myth sebagai lapis makna kedua: masyarakat menganggap tanda tertentu mewakili kebenaran alamiah. Sertifikat K3 lalu dibaca sebagai jaminan keselamatan absolut. Padahal, realitas keselamatan ditentukan oleh budaya K3, supervisi, pelaporan nyaris celaka, housekeeping, dan learning organization. Ketika sertifikat diperdagangkan, mitos itu berubah jadi fetisisme dokumen: kita menyembah lembaran kertas, bukan praktik keselamatan. Ekonomi tanda & rent-seeking, Di semiotika hukum, tanda punya nilai tukar. Saat biaya resmi (PNBP) rendah—KPK menyebut Rp 275.000—tapi “nilai akses” ke status “boleh kerja” sangat tinggi (proyek bisa jalan/ macet), muncullah rente. Harga bayangan Rp 6.000.000 tak membeli kualitas pelatihan, melainkan mempercepat/ meloloskan akses—itulah logika ekonomi tanda yang diselewengkan.
Analisis lebih dari terhadap Form vs substance, Hukum idealnya menyelaraskan form (sertifikat) dan substance (kompetensi nyata & budaya K3). Begitu form bisa dibeli, substansi runtuh: tanda tetap hadir, makna keselamatan absen. Di titik ini, tragedi etis muncul: pekerja, keluarga, dan publik menanggung risiko.
Struktur Tanda dalam Hukum K3 Indonesia, 1. Payung normatif – UU 1/1970: mewajibkan keselamatan kerja di semua tempat kerja. PP 50/2012: “bahasa” sistem manajemen K3 (SMK3) yang harus hidup di perusahaan. Ini “gramatikanya” keselamatan: siapa wajib melakukan apa, kapan, bagaimana, dan oleh siapa dievaluasi. Sub-gramatika teknis – Permenaker spesifik (mis. pekerjaan ketinggian, ruang terbatas, listrik, dll.) menetapkan jenis sertifikasi dan skema kompetensi. Di sinilah tanda (sertifikat) mengunci kewenangan. Arena implementasi – Pelatihan diselenggarakan balai K3/ PJK3/ lembaga berizin. Biaya pelatihan komersial (umumnya Rp 3–7 juta) berbeda dari biaya penerbitan dokumen resmi negara. Ketika dua dunia ini kabur, publik bingung: yang mahal itu belajar atau stempel?
Membaca Modus “Jalur Cepat” sebagai Manipulasi Tanda, Tekniknya (versi KPK): memperlambat/ mempersulit pemrosesan bagi yang hanya bayar resmi, lalu mempercepat bagi yang bayar tarif bayangan. Secara semiotik, pejabat/oknum mengontrol “waktu”—elemen pragmatik yang sangat menentukan makna tanda di dunia nyata (proyek gagal vs. jalan). Waktu menjadi komoditas tanda. Efeknya: Tanda yang harusnya index kompetensi berubah jadi index kedekatan/uang. Publik lalu menafsir ulang: “sertifikat itu bisa diatur.” Ini menghancurkan kepercayaan (trust)—modal sosial utama keselamatan.
Jadi sekali lagi apa yang Perlu Dibenahi? (Rekayasa Tanda, Bukan Sekadar Tambah Sanksi):
1. Pisahkan keras biaya belajar vs biaya negara, Portal publik menampilkan dua kolom jelas: (A) tarif pelatihan (komersial, kompetitif), (B) tarif PNBP penerbitan/registrasi (tetap). Setiap pengumuman resmi wajib menampilkan referensi tarif PNBP agar publik punya jangkar makna. (Prinsip semiotik: konteks mengikat makna.),
2. Verifiable credentials (VC) + registri publik real-time Sertifikat berbentuk credential digital dengan hash/QR yang memetakan siapa menguji, kapan, materi apa, proktor siapa, nilai berapa. Tanpa metadata, tanda gampang jadi fetiš. (Indexikalitas diperkuat → makna kembali ke kompetensi.),
.
3. Rantai-bukti (audit trail) yang tak bisa dinego, setiap langkah—pembayaran PNBP, unggah dokumen, timestamp, persetujuan pejabat—tampak di dasbor pemohon & pengawas. Log terbuka mengurangi ruang interpretasi samar-samar (sunlight as disinfectant dalam semiotika: transparansi sebagai konteks penutup ambigu).
Arsitektur antrian acak & blind review,mPejabat/asesor tak memilih berkas; sistem mengacak & blind sebagian informasi identitas agar kedekatan tak menjadi indeks makna. Ini mengganggu “bahasa rahasia” jalur cepat . Kontrak tanda: SLA dengan sanksi.
Cantumkan Service Level Agreement berdasar hukum (berapa hari maksimal, bukti apa yang sah). Jika meleset tanpa alasan sah, otomatis eskalasi & pengurangan biaya; jika ada “balasan cepat berbayar”, mudah terdeteksi sebagai anomali. Publikasi statistik & red flags Mingguan: waktu rata-rata terbit, outlier, perbandingan balai/provinsi. Data ini menjadi teks sekunder yang membatasi storytelling liar di pasar, memulihkan makna tanda secara sosial. Bahasa risiko di hulu Campaign “Ape bende K3?” harus menekankan: sertifikat = izin bertindak + jejak kompetensi, bukan jimat kebal bencana. Bawa studi kasus nyaris celaka; geser makna dari “kertas” ke kapasitas tim.
Menjaga Martabat Tanda: Pelajaran Moral (dan Praktis), Sertifikat K3 itu bukan sekadar kertas; ia tindak performatif yang mengubah status hukum dan membuka akses kerja berisiko tinggi. Ketika tanda itu diperjualbelikan, bahasa hukum patah: kalimat “kompeten & selamat” berubah jadi “mampu bayar & dekat.” Itu yang membuat skandal ini terasa getir—bukan hanya dugaan tindak pidananya, melainkan kerusakan makna yang ia tinggalkan. Jawaban atas pertanyaan pamungkasmu—“apakah harus serumit itu atau sengaja dirumitkan?”—dalam kacamata semiotika hukum adalah: kompleksitas memang perlu untuk mutu & akuntabilitas, tetapi ketakjelasan adalah ladang subur rente. Maka tugas kita bukan meniadakan kompleksitas, melainkan menjinakkan ambiguitas: memperjelas tarif, alur, waktu, metadata, dan jejak digital sehingga tanda kembali setia pada substansi keselamatan. “Camane orang Disnaker Kalbar, tul ndak?” Jika visi kita sama—pekerja pulang selamat, proyek berkualitas, martabat hukum terjaga—maka bahasa yang harus kita bangun bukan “jalur cepat”, melainkan jalur jelas: terang biayanya, terang prosesnya, terang maknanya.
Rujukan kunci narasi diatas adalah Pernyataan KPK soal tarif resmi Rp 275 ribu vs Rp 6 juta, penetapan 11 tersangka, peran Noel, dan periode 2019–2025. UU No. 1/1970 (keselamatan kerja) & PP No. 50/2012 (SMK3). Contoh biaya pelatihan Ahli K3 Umum (komersial) 2024–2025 untuk konteks pasar.